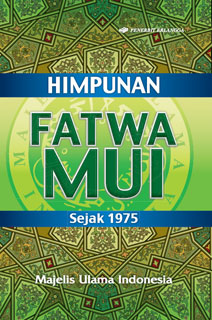
 Perilaku korupsi di Indonesia mungkin layak disamakan dengan dunia klenik dan perdukunan. Paling minimal, keduanya sama-sama erat dengan hal yang serba gaib. Cukup aneh memang kedengarannya, tapi itu suatu kenyataan pahit yang harus ditelan bulat-bulat bangsa ini.
Perilaku korupsi di Indonesia mungkin layak disamakan dengan dunia klenik dan perdukunan. Paling minimal, keduanya sama-sama erat dengan hal yang serba gaib. Cukup aneh memang kedengarannya, tapi itu suatu kenyataan pahit yang harus ditelan bulat-bulat bangsa ini.
Banyak kasus korupsi yang cepat sekali tercium bau busuknya, tapi sulit ditemukan sumber bau atau bangkainya. Sampai hari ini masih banyak kasus mega korupsi yang tak kunjung terselesaikan. Sebut saja, misalnya, kasus bailout Bank Century yang diduga merugikan negara hampir Rp 7 triliun. Dugaan korupsi yang terkait dengan proses bailout tersebut makin menguat menyusul dimenangkannya mantan investor Bank Century, Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi yang melawan pemerintah di dewan Arbitrase Internasional—Internasional Center for Settlement of Investment Disputes (Tribunnews http://www.tribunnews.com/2011/09/10/hesham-rafat-menang-di-pengadilan-arbitrase).
Bukan hanya kasus Bank Century, kasus dugaan mega korupsi lain seperti “rekening gendut” pejabat tinggi Polri, mafia perpajakan yang mengemuka lewat kasus Gayus Tambunan, dan paling mutakhir, dugaan korupsi dalam penetapan APBN di DPR, yang terendus lewat kasus penyuapan pembangunan Wisma Atlet yang melibatkan mantan anggota DPR, Muhammad Nazaruddin, juga belum terungkap atau belum menyentuh otak pelaku atau “pemain” sesungguhnya yang diduga berasal dari para elit partai berkuasa saat ini.
Asas Praduga Tidak Bersalah
Sulitnya pemberantasan korupsi di Indonesia, selain tentu saja karena lemahnya penegakan hukum oleh pemerintah dan otoritas hukum, ditengarai juga karena penanganannya yang masih biasa-biasa saja. Maksudnya, belum ada terobosan hukum yang diupayakan oleh pemerintah agar korupsi benar-benar dapat diberantas.
Dalam upaya mencari keadilan, asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent) menjadi kredo hukum utama. Prinsip ini menempatkan setiap orang berstatus tidak bersalah di muka hukum sampai ada fakta yang membuktikannya bersalah. Prinsip ini berlaku hampir di belahan bumi mana pun. Tujuannya, untuk melindungi hak azasi manusia seseorang yang tidak boleh dikurangi dalam situasi dan kondisi apa pun. Nilai ini dijamin oleh nilai-nilai agama, budaya, maupun tata pergaulan internasional.
Sayangnya, prinsip tersebut tidak bekerja secara maksimal begitu dihadapkan pada kasus-kasus korupsi di Indonesia yang serba gaib. Para elit pemerintah yang terindikasi korupsi mudah sekali berkelit dari jeratan hukum dengan berbagai cara, termasuk mengorbankan anak buahnya. Hal ini dimungkinkan karena setiap pejabat pemerintah yang terindikasi korupsi tidak punya kewajiban untuk membuktikan bahwa harta yang dimilikinya dan istri atau suami serta anak-anaknya benar-benar didapat dengan cara yang halal, terlepas apakah kekayaannya yang berlimpah ternyata tidak seimbang dengan penghasilan jabatannya, pun meski sudah ditambah dari sumber pendapatan lain jika memang ada.
Hadirnya UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memang sempat memberikan secercah harapan dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Kedua undang-undang tersebut memungkinkan dilakukannya semacam pembuktian terbalik oleh terdakwa di muka pengadilan. Sayangnya, secara operasional undang-undang tersebut berlaku sekadar untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bagi seorang terdakwa. Undang-undang tersebut tentu saja tidak dapat menjerat seseorang yang berstatus sebagai terduga, apalagi jika masih sebagai tersangka.
Pembuktian Terbalik
Beberapa pihak memang mengkhawatirkan pemberlakuan pembuktian terbalik akan mengurangi bahkan melenyapkan hak azasi yang dimiliki oleh seseorang. Namun, banyak pula pihak yang menganggap bahwa justru untuk kasus-kasus korupsi, penggelapan, dan pencucian uang yang pembuktiannya kerap sulit dilakukan, hal itu perlu diatur dalam undang-undang yang lebih jelas dan spesifik.
Salah satu pihak yang menganggap perlu diterapkannya asas pembuktian terbalik untuk kasus-kasus kasus korupsi, penggelapan, dan pencucian uang adalah Majlis Ulama Indonesia (MUI). Dalam Musyawarah Nasional VIII, Komisi Fatwa MUI melahirkan fatwa mengenai Penerapan Asas Pembuktian Terbalik (Lihat buku Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, Jakarta: Erlangga, 2011, h. 547-554).
Preseden hukum yang dijadikan referensi oleh MUI adalah kasus dakwaan tindak perkosaan yang dituduhkan kepada Nabi Yusuf AS. Dalam pengadilan, Nabi Yusuf AS pun membuktikan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepadanya tidak benar. Koyaknya pakaian beliau di bagian belakang, bukan di bagian depan, memperkuat hal itu. MUI juga mengutip ijtihad yang pernah dilakukan Umar bin Khattab ketika pada suatu ketika beliau meminta pembuktian kepada Abu Hurairah atas harta yang dimilikinya, apakah didapat dengan jalan halal atau sebaliknya.
Meski secara umum, seorang terdakwa dalam mekanisme hukum Islam hanya dituntut bersumpah untuk menolak segala tuduhan terhadapnya. Mengacu pada dua preseden hukum di atas, dalam pertimbangannya MUI menilai bahwa pembuktian terbalik sangat diperlukan. Terutama untuk memudahkan pengusutan kasus-kasus yang pembuktian materialnya sulit dilakukan, seperti kasus korupsi, penggelapan, dan pencucian uang. [Andriansyah]











